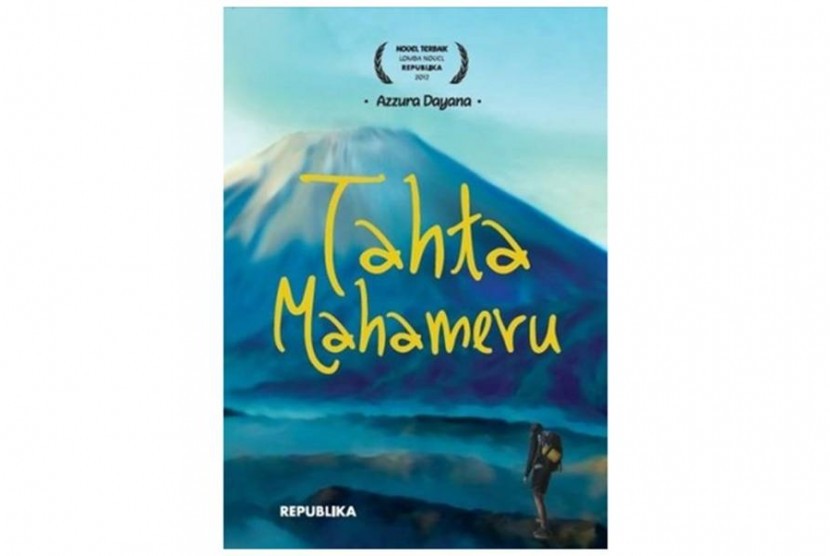Gotcha..! Setelah mencoba mengunyah halaman-halaman pertama Tahta Mahameru, akhirnya saya menemukan alasan untuk mewajibkan diri membaca buku ini dengan cermat sampai halaman terakhir. Menelisik kata demi kata yang Azzura Dayana tuturkan saat membawa pembaca berkelana dari Magelang hingga Tanjung Bira. Membingkai sebuah persahabatan unik antara Faras dan Ikhsan, juga Mareta, melalui tiga pertanyaan besar: sebelas alasan untuk shalat, apakah Allah ada di puncak Mahameru, dan apakah dendam akan terpuaskan dengan membunuh. Sungguh pertanyaan yang berat.
Ikhsan, ”raja” yang membulatkan tekad menaklukkan Semeru lagi dan lagi untuk meredam dendam yang berkecamuk di hatinya, meski ia tahu kesumatnya tak akan pernah sirna. Anak dari sebuah keluarga broken home lantaran sang ayah lebih memilih kembali ke Nyonya Junita, istri tuanya yang diam-diam melancarkan teror membabi buta kepada ibu Ikhsan. Ikhsan hadir sebagai sosok yang luar biasa ketus, tak tahu diri, dan menyebalkan bagi setiap orang yang mengenalnya. Bahkan seperti yang diakui Ikhsan, semakin hari, jumlah temannya semakin berkurang. Ikhsan miskin teman. Dan ia tak mau tahu alasannya.
Faras, seorang gadis sederhana penggila Kahlil Gibran dari Desa Ranu Pane di Gunung Semeru, bertemu secara tak sengaja dengan pendaki aneh bernama Ikhsan yang nyaris bertengkar dengan Fikri, rekan sesama pendakinya. Pertemuan selanjutnya terjadi berbulan-bulan kemudian dan sekali lagi Faras harus menelan ketidakmengertiannya atas sikap Ikhsan. Sungguhpun begitu, Faras tetap mencoba memahami dan tidak mempermasalahkan. Sampai-sampai, si Sinis Ikhsan pun bergumam dalam hati, ”Apa memang benar ada,manusia yang dilahirkan tanpa secuil rasa dendam di hatinya, seperti gadis ini?”
Mareta, gadis tomboy dari Jakarta yang minggat dari rumah dan memilih berpetualang a la backpacker sebagai pelarian karena orang tuanya ricuh. Perjalanannya ke Borobudur mempertemukannya dengan Faras yang tanpa sangaja mendengar percakapan telepon Mareta tentang monster bernama Raja Ikhsan. Benar-benar kebetulan yang menjadi awal sebuah perjalanan panjang melintasi Laut Jawa menuju Bumi Celebes.
Ya, novel Tahta Mahameru adalah cerita tentang perjalanan. Perjalanan para tokohnya dalam mencari jawaban dan hakikat kehidupan: persahabatan, kasih sayang, dan memaafkan. Disajikan dalam lika-liku perjalanan ke Candi Borobudur, Ranu Pane, Ranu Kumbolo, Bulukumba, Makassar, dan Jakarta. Dipertajam dengan bumbu keindahan alam Gunung Bromo, adat istiadat masyarakat Bugis, syair para pujangga maupun petikan lirik lagu menjadikan Tahta Mahameru sebuah novel yang kaya warna.
Petikan puisi-puisi Kahlil Gibran yang sering menjadi kutipan Faras, terasa memberikan sentuhan romantisme pada persahabatan Faras dan Ikhsan. Misalkan, ”Yang paling dekat dengan hatiku adalah seorang raja yang tidak memiliki singgasana dan seorang miskin yang tidak tahu caranya mengemis,” atau ”Suara kehidupan di dalam diriku tidak dapat menyentuh telinga kehidupan dalam dirimu, tetapi marilah kita berbicara agar kita tidak akan merasa kesepian.”
Bahkan, sosok Ikhsan yang dinginpun ternyata menimpan romantisme puisi yang ia sampaikan ke Faras, di bawah purnama Ranu Pane, ”Mencintai air harus menjadi ricik.. Sampai-sampai hujan yang kesekian kerap juga menemani perjalanan cinta kita. Hujan di langit itu. Hujan di matamu.” Apakah memang ada seulas kisah cinta dalam persahabatan mereka? Pembaca hanya bisa mengira-ira karena penulis sengaja menggantungkannya di akhir cerita.
Penguasaan penulis akan keelokan alam dan seluk beluk pendakian dan perjalanan ke Ranu Pane, Ranu Kumbolo, Savanna Oro-oro Ombo, Kalimati, Cemoro Kandang, Gunung Bromo, Makassar, Tanjung Bira, dan tentu saja puncak Mahameru benar-benar mengajak pembaca ikut menyaksikan bukti ke-Maha-Kuasa-an Allah. Hal itu terasa sekali saat penulis mengisahkan pendakian Faras, Mareta, Ikhsan, dan Pak Daud saat semua tokoh tersebut akhirnya bertemu di Ranu Pane dan berangkat menuju puncak Mahameru.
Simaklah pula bagaimana penulis menggambarkan detil pendakian ke Mahameru, ”Ya, tanjakan setelah pos tiga ini mempunyai riwayat cukup banyak dalam menggelincirkan para pendaki. Tidak ada pepohonan besar di sekitarnya, hanya ada rumput-rumput, sehingga untuk mendakinya terkadang kita harus membungkuk dan meletakkan tangan di tanah.”
Hal itu tidaklah terlalu mengherankan. Azzura Dayana adalah pecinta travelling, fotografi, dan membaca. Penulis muda yang produktif ini pun seringkali menyisipkan unsur kearifan lokal (indigenous knowledge) sebagai ciri khas tulisannya, termasuk di Tahta Mahameru. Penggunaan kata Daeng, Ando, Ambe, dan istilah-istilah daerah juga berhasil memperkuat setting lokasi yang sedang dimainkan dalam setiap bab.
Penulis juga mencoba menyuguhkan infomasi mengenai pernak-pernik adat dan masyarakat setempat dengan deskripsi yang, di beberapa bagian, sayangnya justru cenderung untuk dilewati oleh pembaca karena menggunakan bahasa text book. Misalkan penjelasan tentang Desa Kajang dan Ammatoa.
Uniknya, penulis menyuguhkan Tahta Mahameru sebagai sebuah novel dengan gaya tuturan yang kompleks. Ketiga tokoh utamanya – Ikhsan, Faras, dan Mareta – secara bergantian digunakan sebagai sudut pandang penuturan. Pilihan sudut ini sangat membantu pembaca memahami sisi kejiwaan, menyelami cara berpikir, dan merasakan konflik internal yang ada dalam diri masing-masing tokoh. Pada akhirnya, novel ini menyuguhkan karakter tokoh utama yang berhasil dibangun penulis dengan alami dan terasa lebih nyata.
Faras mengawalinya di bab pertama, Arupadhatu. Seharusnya aku tiba di sini tiga hari yang lalu, 3 Juli, saat e-mail itu kuterima. E-mail dari Ikhsan pulalah yang menjadikan Faras membulatkan tekad untuk menjumpai Ikhsan sekali lagi, di manapun itu, dan menuntaskan segala tanya yang pernah terlontar. Ya Rabb, berilah kesempatan padaku untuk memberikan ia jawaban yang aku bisa. Aku sungguh tidak ingin dia melakukan hal yang tidak baik. Berilah kami kesempatan bertemu, ya Rabb. Jika takdirnya bukan di tanah Sulawesi ini aku tidak keberatan. Aku sabar menunggu hingga datang waktunya Engkau meng-ijabah doaku.
Perjalanan Faras hingga Tanjung Bira memang membuahkan pertemuan, namun bukan dengan Ikhsan. Faras bertemu dengan Aros, adik Fikri, yang pernah bertemu Ikhsan sebulan sebelum Faras datang. Aros-lah yang bercerita kepada Faras, betapa sosok Ikhsan kini sungguh jauh dari sangkaan Faras.
”Daeng Ikhsan orang yang sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepadanya,”
kata Aros.”Marah?”
Aros balik tanya.”Sekali pun tidak, Daeng.”
”(Kata-katanya) Selalu baik. Itulah sebabnya Ando sangat menyayangi Daeng Ikhsan.”
Keterkejutan Faras-pun menular kepada Mareta yang ternyata adalah adik tiri Ikhsan. Monster itu bisa berkata-kata baik dan berterima kasih? Itu keajaiban atau keanehan? Ya, sulit buat gue percaya. Penulis menggunakan kata sapaan loe-gue saat menempatkan sudut pandang Mareta. Pilihan kata yang nampaknya bermaksud menegaskan sosok gaul dan anak Jakarta yang dilekatkan pada tokoh Mareta.
Jujur saja, penggunaan kata "loe-gue" di novel ini terasa agak janggal di mata saya, terlebih saat digunakan dalam deskripsi cerita. Akan lebih pas jika kata "loe-gue" dicukupkan pada kalimat-kalimat percakapan langsung dan menggunakan kata ”(a)ku” untuk mewakili pemikiran Mareta dalam deskripsi.
Gaya tuturan "loe-gue" justru tidak dilekatkan pada sudut pandang Ikhsan yang digambarkan memiliki karakter kasar dan keras. Tanpa diduga, sosok Ikhsan seolah mengalami metamorforsis menjadi sosok yang lebih bijak setelah melalui babak kesumat berdarah kepada Nyonya Junita dan mendaratkan Ikhsan di penjara selama beberapa bulan. Lucu saja ketika kusadari ada benih-benih kebijakan dalam pemikiranku yang biasanya frontal ini. Ataukah ini bekal yang kuperoleh dari penjara? Bahkan belakangan, baru terkuak kebenaran bahwa e-mail yang diterima Faras dikirim oleh Aulia, kakak Mareta, dengan mengatasnamakan Ikhsan.
Alur cerita maju-mundur yang dipilih penulis berhasil menghadirkan sensasi petualangan tersendiri bagi pembaca. Berawal di Borobudur, mundur ke Ranu Pane, maju ke Surabaya, mundur ke Sulawesi Selatan, maju ke Tanjung Bira, mundur dan maju lagi ke Jakarta, maju ke Tanjung Bira, konstan mengalir maju ke Banjarmasin, Tanjung Bira, Surabaya, dan berakhir di Mahameru. Membaca novel ini sepotong-sepotong hanya akan membuat pembaca dibingungkan dengan alur cerita. Penulis sukses menyeret pembaca untuk membaca halaman demi halaman yang ingin mengetahui perjalanan "Tahta Mahameru" seutuhnya.
Jika novel "Tahta Mahameru" pada akhirnya ditetapkan sebagai salah satu Novel Terbaik Lomba Novel Republika 2012, maka menurut saya hal itu sangat pantas. Kepiawaian penulis menyajikan berbagai amanat dalam kemasan travelling, perenungan para tokoh, dan petikan kata-kata bijak dari berbagai sumber patut diacungi jempol. Referensi dan pengalaman penulis tentu lebih dari cukup untuk dapat meramu semua data dan informasi agar Tahta Mahameru menjadi novel perjalanan yang menggugah hati.
Sebagai sebuah karya, kelincahan penulis dalam bermain kata dan menjalin cerita benar-benar wajib ditiru oleh para penikmat dunia tulis-menulis. Benar-benar novel bagus yang semakin dibaca akan menimbulkan semakin banyak pemahaman tentang banyak hal. Salut untuk Azzura Dayana!
Sedikit ketidaknyamanan saya rasakan saat membaca halaman 275-279 dan 320-322, di mana jenis huruf yang digunakan penerbit novel ini mendadak berubah menjadi Times New Roman. Meskipun bukan hal yang fundamental, namun syok mata yang saya rasakan akibat inkonsistensi ini cukup mengusik kenikmatan penjelajahan "Tahta Mahameru".
Lantas, apakah alasan saya membaca Tahta Mahameru terjawab sampai dengan berakhirnya cerita? Apakah Faras tetap memberikan jawaban bahwa Allah hadir di mana-mana pada pertanyaan Ikhsan? Sungguh saya khawatir penulis terjebak pada pemahaman bahwa Allah hadir di mana-mana adalah benar-benar ajaran Islam yang sesungguhnya. Padahal Allah sendiri berfirman tentang singgasananya, Arsy, ”Yang Menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.”
Syukurlah, penulis dengan bijak menyampaikan melalui Faras, ”Kata apa lagi yang sanggup kita ungkapkan untuk memuji Allah? Untuk semua kehebatan penciptaan ini. Padahal Mahameru baru satu bagian kecil saja dari seluruh ciptaan-Nya di semesta raya...” Ikhsan pun digambarkan puas dengan jawaban yang menyiratkan bahwa Mahameru hanyalah ciptaan Allah, bukan tahta-Nya.
Jawaban Faras akan terasa lebih manis jika saja penulis menyisipkan salah satu ayat Qur’an Surat al A’raf, di mana terjemahan al A’raf telah penulis gunakan sebagai judul bab terakhir novel "Tahta Mahameru": Tempat Tertinggi. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas Arsy. Pertanyaan Ikhsan yang paling mendasar ini, dan mungkin juga pertanyaan yang sangat ditunggu jawabannya oleh pembaca yang sedang mencari hidayah, insya Allah akan tandas terjawab. Wallahu a’lam.
Salatiga, 30 Mei 2012
Untuk suamiku, dengan segenap cinta,
Rekomendasi
-
Selasa , 14 Feb 2023, 16:19 WIB

Konser 'Kenopsia', Coba Bangkitkan Dunia Perkusi Tanah Air dari Mati Suri
-
-
 Selasa , 14 Feb 2023, 15:57 WIB
Selasa , 14 Feb 2023, 15:57 WIBHijrah, Aming Meminta Doa Agar Tetap Istiqomah
-
 Selasa , 14 Feb 2023, 15:19 WIB
Selasa , 14 Feb 2023, 15:19 WIBSerial 'Salma’s Season' Jelajahi Keberagaman Muslim di Australia
-
 Selasa , 14 Feb 2023, 14:32 WIB
Selasa , 14 Feb 2023, 14:32 WIBJangan Kaget, Begini Cara 'Aneh' Jerapah Jantan Ajak Kawin Betina
-
 Selasa , 14 Feb 2023, 14:05 WIB
Selasa , 14 Feb 2023, 14:05 WIBHenry Cavill tak Ada di Trailer Film The Flash, Penggemar Kecewa
-